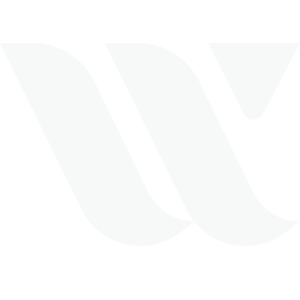Dua orang pelajar diduga mengalami penganiayaan oleh Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Masias Siahaya (MS) di Kota Tual Maluku.
Satu korban, Arianto Tawakal (14), dilaporkan meninggal dunia setelah diduga dipukul di bagian kepala. Sementara Najril Karim Tawakal (12) mengalami luka pada tangan kanan.
Fenomena “mabuk seragam” atau arogansi akibat atribut kekuasaan merupakan diskursus sosiopsikologis yang mendalam.
Di Indonesia, selembar kain bukan lagi sekadar pelindung tubuh atau identitas profesi, melainkan sering kali bertransformasi menjadi “zirah” moral yang merasa berhak berada di atas hukum. Hal ini menciptakan jarak antara pemakai seragam dengan masyarakat yang seharusnya dilayani.
Secara psikologis, fenomena ini berkaitan dengan Enclothed Cognition, sebuah teori yang menyatakan bahwa pakaian yang kita kenakan mempengaruhi proses psikologis dan cara kita memandang diri sendiri.
Di Indonesia, penghormatan terhadap simbol sering kali melampaui penghormatan terhadap fungsi. Ketika seseorang mengenakan seragam yang diasosiasikan dengan otoritas absolut, mereka cenderung menginternalisasi karakteristik “kekuatan” tersebut secara berlebihan.
Budaya feodalistik yang masih mengakar membuat masyarakat cenderung tunduk pada simbol kekuasaan. Akibatnya, seragam dianggap sebagai kelas sosial instan yang memberikan akses khusus dan privilege di ruang publik.
Jika institusi tidak tegas menghukum arogansi anggotanya, seragam tersebut beralih fungsi menjadi tameng impunitas.
Di banyak negara maju, aparat keamanan melakukan demistifikasi. Sebagai contoh, polisi di Inggris (The Met) secara historis didesain untuk tidak terlihat seperti militer.
Mereka menggunakan seragam yang lebih mendekati tampilan warga sipil profesional dan sering kali tidak bersenjata api dalam patroli rutin.
Tujuannya jelas: agar masyarakat melihat mereka sebagai rekan dalam menjaga ketertiban, bukan sebagai kekuatan pendudukan.
Di negara seperti Finlandia atau Denmark, pendidikan polisi sangat ketat dan setara dengan pendidikan sarjana yang mendalam. Kurikulum mereka tidak hanya fokus pada taktik fisik, tetapi sangat menekankan pada psikologi massa, hak asasi manusia, dan resolusi konflik.
Di sini, arogansi dianggap sebagai bentuk kegagalan intelektual. Seorang petugas yang menggunakan seragam untuk mengintimidasi dianggap tidak profesional dan kurang terdidik.
Penggunaan teknologi seperti kamera tubuh (body-worn cameras) di negara maju berfungsi untuk “menjinakkan” potensi arogansi. Di sana, seragam justru membuat pemakainya merasa selalu diawasi oleh publik dan hukum.
Seragam adalah kontrak kerja yang mengikat mereka pada standar etika yang lebih tinggi daripada warga biasa, bukan malah membebaskan mereka dari aturan.
Psikolog Philip Zimbardo dalam studinya menunjukkan bagaimana peran dan seragam dapat mengubah perilaku seseorang menjadi destruktif jika tidak dibatasi oleh sistem pengawasan yang kuat.
Di masyarakat yang pendidikannya maju, disadari betul bahwa arogansi seragam sebenarnya adalah tanda dari kematangan emosional yang rendah.
Seseorang yang merasa “lebih besar” hanya karena pakaiannya menunjukkan bahwa jati diri mereka sebenarnya rapuh jika tanpa atribut tersebut.
Di negara maju, kehormatan tidak didapatkan dari ketakutan orang lain saat melihat seragam, melainkan dari kompetensi dan integritas pemakainya.
Mereka memahami bahwa semakin tinggi otoritas yang diberikan oleh seragam tersebut, semakin besar pula beban tanggung jawab yang harus dipikul di hadapan publik.
Pergeseran dari budaya “dilayani” menjadi “melayani” memerlukan lebih dari sekadar perubahan aturan, ia memerlukan revolusi pendidikan dan penguatan pengawasan sipil.
Di negara maju, pendidikan tinggi membuat orang sadar bahwa seragam adalah beban pengabdian, bukan alat untuk membusungkan dada di jalan raya apalagi untuk memukuli duang orang pelajar yang masih berusia belasan tahun.
Penulis Adalah Ketua Departemen Pendidikan Centre Of Local Economy And Politics Studies Jember Alamat : Perum Griya Mangli Indah Blok BE 10 Kaliwates Jember Telp : 082229170915